Simpul Puitis
7 Juni 2018 Tinggalkan komentar
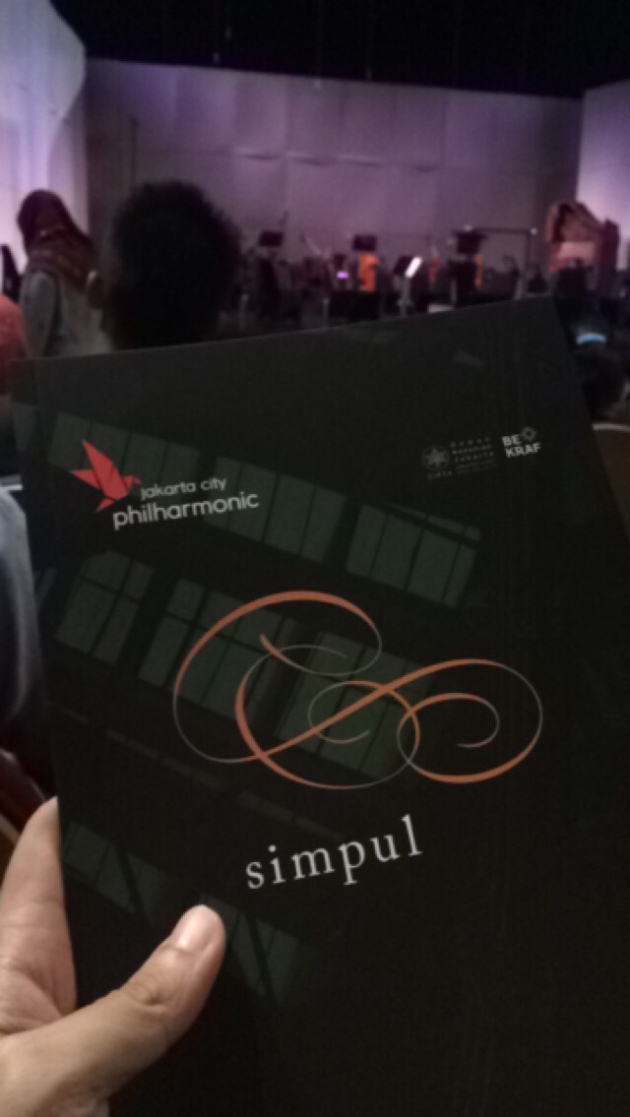
Gue merasa beruntung sekali dalam seminggu bisa nonton konser 2 orkestra besar Jakarta, yang satu Jakarta Simfonia Orchestra, satu lagi Jakarta City Philharmonic, dan keduanya memiliki kesan yang mendalam. Kedua konser inilah yang membuat gue makin yakin perkembangan dunia orkestra tanah air menjadi semakin menjanjikan.
Tentang JSO yang hanya memainkan 2 karya simfonik (Mozetich – The Passion of Angels dan Berlioz – Symphonie Fantastique) sudah gue bahas di status Facebook sebelumnya. Tapi yang menarik untuk kembali diungkit adalah bahwa ada beberapa pemain instrumen gesek yang main di kedua konser ini, dan sensitivitas mereka semakin tinggi tak hanya dalam bermain dan mendenyutkan musiknya bersama, tapi juga dalam saling mendengarkan satu sama lain, sehingga setiap musisi bisa memahami fungsi dari bunyi instrumennya masing-masing dalam membentuk anyaman dengan bunyi instrumen-instrumen lainnya.
Konser malam tadi adalah kali pertamanya JCP menjual tiket, dan kali pertamanya mereka hanya menggunakan ensembel gesek dalam pertunjukannya. Ada tantangan yang sangat tinggi dalam menggunakan instrumentasi seperti ini, yaitu bahwa musik yang dihasilkan harus mengantarkan energi yang sama besarnya kepada penonton walau tanpa kehadiran alat-alat tiup dan perkusi. Konsekuensinya, tak hanya dibutuhkan stamina yang tinggi dari para pemain, tapi juga kepekaan yang tinggi dalam mengusahakan setiap divisi instrumen (biola 1, biola 2, viola, cello dan kontrabas) untuk bisa solid secara ritme maupun secara intonasi nada.
Memang masih ada yang bisa disempurnakan di aspek ini, namun hal yang tak kalah pentingnya adalah intensitas dari setiap nada ataupun setiap tanda istirahat yang dibunyikan (dan tidak dibunyikan). Hal ini sangat terasa sejak lagu Indonesia Raya dimainkan sebagai pembuka konser. Baru kali ini gue denger lagu kebangsaan kita ini dimainkan hanya dengan orkestra gesek, dan ternyata justru ada keharuan yang lebih dalam terasa tanpa kehadiran alat tiup dan perkusi, dan penonton bagai disiapkan untuk merasakan kesyahduan konser malam ini.
Tak hanya syahdu, beberapa nomer seperti Serenade karya Edward Elgar dan Divertimento karya Bartok menantang para musisi dan konduktor untuk menghasilkan musik yang menyalak, berjingkat, melompat, juga galak di banyak momen. Tapi terutama di dua nomer terakhir, Serenade karya komponis Swedia, Dag Wiren; dan Adagietto dari Simfoni ke-5 karya Gustav Mahler, konduktor Budi Utomo Prabowo berhasil mengajak para musisi JCP menunjukkan penguasaan interpretasi mereka yang lebih berani lugas dalam artikulasi nada-nadanya, dengan kedalaman musikalitas yang lentur untuk menghasilkan kontras dinamika dan warna yang dibutuhkan di sana-sini.
Memang sebenarnya kalau kelugasan dan kelebaran jangkauan dinamika yang sama bisa dihasilkan di nomer-nomer lainnya – terutama di karya Budhi Ngurah, Tarian Kabut Kintamani, yang banyak mengadaptasi jalinan alat-alat gamelan ke dalam ensembel gesek di dalamnya – pasti akan lebih menguras energi para pemain tapi akan membuat pengalaman konser hari ini lebih tak terlupakan lagi.
Apresiasi tinggi juga perlu dialamatkan kepada para prinsipal, terutama Danny Robertus (biola 1), Obrin Kussoy (viola) dan Ade Sinata (cello) yang mengantarkan porsi-porsi solo mereka dengan sangat memukau dan proporsional, dengan kelenturan warna bunyi yang memungkinkan mereka untuk bisa tetap berbunyi selaras ketika harus kembali berbunyi tutti bersama rekan-rekan divisinya.
Perlu disebutkan juga adalah Vincent Wiguna yang memainkan orgel bambu yang keunikan warna bunyinya berhasil membuat Adagio in g minor karya Albinoni/Giazotto dan Canon in D karya Pachelbel menjadi lebih sejuk tropikal. Juga harpis Carlin Eureka Yasin yang turut mengiringi dengan dinamika dan artikulasi yang pas dalam Adagietto karya Mahler yang banyak menuntut kesigapan akan fluktuasi tempo.
Adagio for Strings karya Samuel Barber sangat pas dipilih sebagai persembahan untuk mengenang mereka yang menjadi korban kekerasan atas kemanusiaan yang terjadi belum lama ini di beberapa tempat di Indonesia. Secara pribadi, gue merasa sebenarnya karya ini bisa lebih lirih lagi dimainkan, terutama di titik klimaks sebelum bagian Coda. Namun tetap tidak menghilangkan kesyahduan yang sama yang ingin dihadirkan JCP malam ini.
Sesuai penjelasan konduktor Budi Utomo Prabowo, tema Simpul dalam konser malam ini memang dirasa cocok mewakili pernyataan sikap JCP sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya. Alat-alat gesek memiliki dawai yang hanya akan bisa dibunyikan jika diregangkan dan diikat dengan simpul di kedua ujungnya. Apa yang kita butuhkan sebagai masyarakat adalah simpul demi simpul yang mampu mengikat individu-individu yang berbeda satu sama lain ini dalam suatu kesamaan. Dan memang kesamaan nasib biasanya memudahkan kita untuk bisa merasa sejajar dengan sesama.
Menutup konser malam ini, JCP memainkan Di Bawah Sinar Bulan Purnama karya penulis lagu R. Maladi yang diaransemen oleh Jozef Cleber – yang juga mengaransemen Indonesia Raya yang membuka konser ini. Secara puitis, karya ini seperti menekankan lagi tentang simpul tadi: kita semua berbagi kehidupan di bawah sinar bulan yang sama pula.
Selamat menjadi (sesama) manusia!







